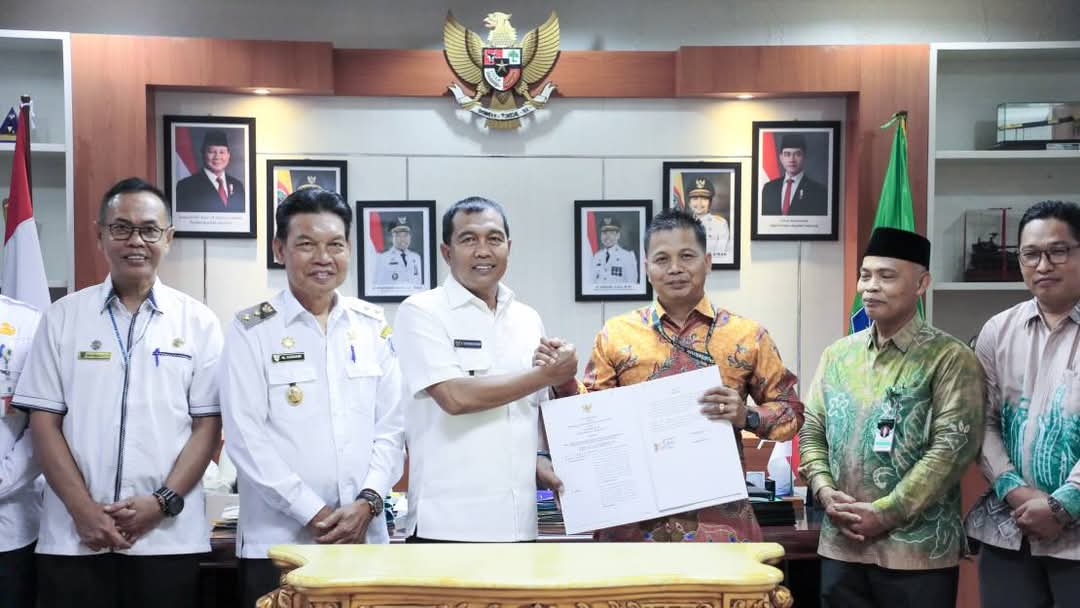bakabar.com, JAKARTA - Pendidikan yang sering dinilai sebagai wadah untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, nyatanya tidak terlepas dari konstruksi sosial yang banyak menyudutkan perempuan.
Pemikiran perempuan jarang dijadikan referensi sumber ilmu, karena praktik misoginisme yang menganggap perempuan tak layak untuk didengar, dan tidak dianggap mampu untuk berfikir.
Strukturisasi pendidikan di Indonesia contohnya, mulai dari pemilihan tokoh-tokoh pahlawan, hingga sumber literasi, mayoritas masih dipegang oleh paham maskulinitas. Padahal, pengalaman perempuan tentu sangat penting dalam tataran sosial. Absennya pemikiran feminis ini juga bisa menyebabkan diskriminasi lain di lingkup pendidikan.
Baca Juga: Mengapa Perlu Pendidikan Seks sejak Usia Dini?
Ikhaputri Widiantini, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia itu menjelaskan pada papernya jika nuansa misoginis dalam perkembangan pemikiran filsafat membantai kesempatan perempuan dikenal sebagai filsuf.
Ia juga menerangkan, “Jangankan dikenal pemikirannya, filsafat populer bahkan memiliki kecenderungan meminggirkan perempuan,” tulisnya pada terbitan Jurnal Perempuan Agustus 2022.
Penetrasi pemikiran feminisme perlu disegerakan, hal ini lantaran dominasi pemikiran laki-laki pada bangku pendidikan juga melahirkan diskriminasi dan perebutan ruang bagi perempuan.
Baca Juga: Dinas Pendidikan Depok Bantah Tudingan Menelantarkan Siswa SDN Pondok Cina 1
Menurut Widiantini penting melakukan pemberontakan dalam mewujudkan perubahan melalui pedagogi feminis. Penggunaan sistem pedagogi feminis harus dilakukan secara menyeluruh di setiap kelas, sebab meletakkan tanggung jawab pada satu dua kelas tidak akan mendukung perubahan transformatif dalam kurikulum pendidikan.
Berdasarkan percobaan pada silabus pembelajaran yang ia lakukan dengan menyelipkan pedagogi feminis, sebagai landasan sumber pemikiran melalui pengalaman yang ia lakukan di jurusan filsafat Universitas Indonesia, ia menjumpai perubahan yang cukup signifikan.
Baca Juga: Menelisik Resah dengan 'Perempuan yang Berjalan Sendirian'
Mahasiswa yang awalnya hanya mengambil mata kuliah pemahaman gender sebagai syarat untuk menjadi lulus, justru lebih memahami bagaimana konstruksi sosial terjadi. Bahkan dalam percobaannya, beberapa mahasiswa bahkan terlibat aktif dalam pergerakan advokasi keadilan gender.
Diskusi ruang kelas yang ia ampu berkembang menjadi diskusi-diskusi ringan warung kopi, hingga seminar formal dan menginspirasi ruang akademik lain untuk menerapkan hal serupa.
Widiantini membuktikan, pemahaman pengalaman juga pemikiran perempuan, penting berada dalam silabus bangku-bangku pendidikan, untuk memutus jaring diskriminasi yang ada dalam sosial kultur kita.